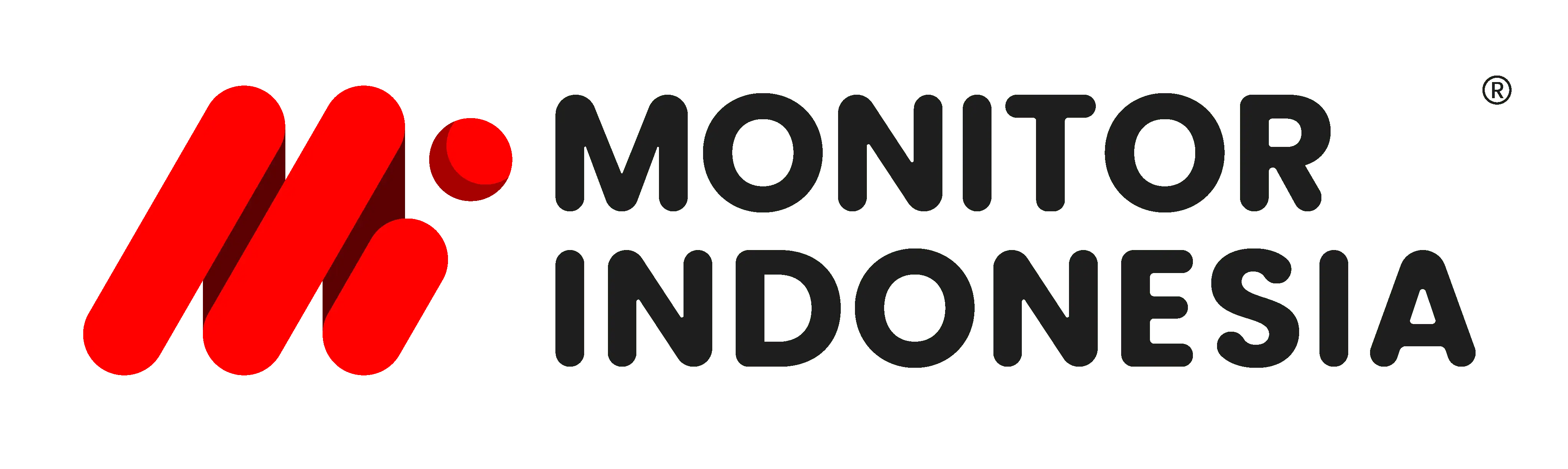Rusak Sangihe Dirundung Tambang

Jakarta, MI - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Greenpeace Indonesia, KontraS, Save Sangihe Ikekendage dan Diaspora Sangihe yang tergabung dalam Koalisi Save Sangihe Island melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (8/10/2025).
Aksi tersebut disertai dengan penyerahan laporan hasil penelitian dari beberapa lembaga akademik yang menemukan fakta lapangan adanya cemaran logam berat yang mengkontaminasi ikan yang berada di perairan Sangihe.
Pulau Sangihe yang kini semakin berada di ambang kehancuran. Di tengah pencabutan izin operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe (TMS) oleh Kementerian ESDM melalui Kepmen ESDM No. 13.K/MB.04/DJB.M/2023, ancaman tambang emas tetap membayangi.
Meski izin lingkungan otomatis gugur, kontrak karya TMS belum dicabut, membuka celah hukum yang dimanfaatkan korporasi untuk terus menekan ruang hidup masyarakat dan ekosistem.
Di balik pencabutan izin, praktik pertambangan ilegal justru kian marak. Dugaan keterlibatan keluarga Bupati Kepulauan Sangihe dan PT TMS dalam jaringan tambang liar memperkeruh situasi.
Dugaan lainnya, selain terlibat sebagai aktor penambang emas ilegal di Sangihe, pejabat daerah justru diduga berkomplot dengan kepentingan ekstraktif, mempercepat kerusakan pulau kecil yang seharusnya dilindungi.
Salah satu indikatornya adalah adanya pertemuan tertutup antara CEO TMS Terry Filbert dan Bupati Michael Thungari pada 29 Juli 2025. Pertemuan ini juga sekaligus menjadi bukti nyata bahwa korporasi masih mencari celah untuk beroperasi.
TMS mengklaim dukungan penuh dari pemerintah daerah, meski secara hukum dan sosial, perusahaan ini telah kehilangan legitimasi. Usai pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Yulianus Selvanus Komaling mengesahkan 30 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sebagian di antaranya diduga berada di Sangihe untuk melindungi praktik pertambangan emas ilegal selama ini yang difasilitasi PT TMS.
Jika ini dibiarkan, Sangihe akan mengalami kiamat ekologis. Riset terbaru Greenpeace Indonesia menunjukkan perairan Sangihe berada dalam kepungan pencemaran berat.
Padahal, perairan Sangihe merupakan ruang pangan dari laut yang penting bagi Indonesia dan dunia.
Sangihe, Pulau Kecil di Ujung Sulawesi yang Harus Diselamatkan
Pulau Sangihe adalah pulau kecil seluas 736,98 km² yang secara konstitusional tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan. Statusnya sebagai pulau kecil menempatkannya dalam perlindungan hukum yang ketat, sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Tidak ada satu pun bentuk pertambangan, termasuk tambang rakyat, yang dapat dibenarkan di wilayah ini.
Meski telah kalah telak di pengadilan dan kehilangan izin operasi serta izin lingkungan, TMS tetap berupaya mencari legitimasi baru. Pertemuan dengan Bupati Sangihe pada Juli lalu menunjukkan strategi korporasi untuk membangun narasi dukungan lokal, meski bertentangan dengan fakta hukum dan aspirasi masyarakat.
Usai bertemu secara diam-diam dengan Bupati Sangihe Michael Thungari, TMS mengunggah siaran pers yang menyatakan korporasi mendapatkan mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sangihe melalui aktivitas pertambangan. Klaim tersebut tak berdasar dan hanya sebatas kedok untuk menjinakkan para aparatur pengurus negara agar tetap dapat beroperasi.
Perlu dicatat, proses hukum yang panjang telah membuktikan bahwa izin operasi produksi PT TMS cacat secara hukum dan harus dicabut. Gugatan warga Sangihe di PTUN Jakarta pada 2021 memang sempat ditolak, namun banding di PTTUN pada 2022 dikabulkan, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam kasasi pada Desember 2022.
Kementerian ESDM kemudian mencabut izin operasi produksi melalui SK No. 13.K/MB.04/DJB.M/2023. Bahkan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT TMS kembali ditolak. Artinya, tidak ada lagi ruang hukum yang sah bagi PT TMS untuk beroperasi di Sangihe.
Namun, alih-alih menghormati putusan hukum, PT TMS justru memilih jalur pembangkangan. Perusahaan ini diduga menjalin kerja sama dengan kontraktor lokal yang tidak memiliki legalitas resmi.
Kerja sama ini dilakukan setelah izin operasi dicabut, dan bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa operasi tambang dilakukan oleh entitas lain. Padahal, kedua kontraktor tersebut tidak terdaftar dalam sistem hukum nasional, dan perjanjian yang dibuat justru memperlihatkan adanya skema pembagian keuntungan yang menguntungkan PT TMS secara ilegal.
Kehadiran tambang emas di pulau kecil seperti Sangihe bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat dan ekosistem. Pulau ini memiliki keterbatasan daya dukung lingkungan yang tidak mampu menanggung beban aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun.
Mengacu pada lanskap ekosistem Sangihe sebagai pulau kecil, sangat jelas bahwa Sangihe bukan zona industri, melainkan zona kehidupan dan konservasi.
Perlindungan pulau kecil harus menjadi prioritas mutlak dalam kebijakan pembangunan dan tata kelola sumber daya alam. Dalam konteks pulau kecil, seluruh bentuk pertambangan harus dihentikan demi menjaga keberlanjutan ruang hidup dan warisan ekologis.
Sangihe sebagai Penyangga Keberlanjutan Ekosistem Global yang Telah Tercemar
Sangihe bukan hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi ekosistem global. Pulau ini merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dunia dan jalur migrasi tuna global, menjadikannya kawasan Ecologically or Biologically Significant Areas (EBSAs) dalam Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) yang diakui dalam COP-CBD 13 di Cancun, Meksiko.
Wilayah perairan Sangihe termasuk dalam Key Biodiversity Areas dunia, menjadi koridor migrasi internasional bagi paus, lumba-lumba, penyu, dan ratusan spesies laut lainnya. Kehadiran tambang emas mengancam keseimbangan ekologis yang telah terbentuk selama ribuan tahun.
Ironisnya, hingga 2024, Sangihe telah kehilangan 996 hektare tutupan pohon yang sebagian besar diduga akibat aktivitas pertambangan ilegal yang tak kunjung berhenti. Dari angka tersebut, 187 hektare merupakan hutan primer basah, menyumbang 19% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.
Penurunan ini menyebabkan pelepasan 82,1 kiloton emisi karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) ke atmosfer. Meski data ini belum memperhitungkan pertumbuhan kembali tutupan pohon, tren kehilangan hutan primer menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap ekosistem tropis Sangihe yang rapuh.
Deforestasi akibat pembukaan lahan tambang tersebut mempercepat kerusakan habitat dan mengganggu siklus migrasi burung. Padahal, Sangihe adalah titik penting dalam jalur migrasi burung dari belahan bumi utara dan selatan, yang mencari tempat tinggal sementara di iklim tropis Indonesia.
Menurut Burung Indonesia, terdapat 262 jenis burung migran yang singgah di Indonesia, dan 12,2% di antaranya dapat dijumpai di Sangihe. Kehadiran tambang akan mengganggu siklus hidup mereka dan memperburuk krisis ekologi global.
Riset terbaru Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa pencemaran logam berat di laut Sangihe telah mengancam ekosistem pangan dan kesehatan masyarakat. Kandungan arsenik, merkuri, dan kadmium ditemukan dalam sedimen laut, mengindikasikan dampak serius dari aktivitas tambang terhadap laut dan kehidupan manusia.
Berdasarkan temuan Greenpeace Indonesia, kandungan arsenik di sedimen laut Sangihe mencapai 1,5 mg/kg, melebihi ambang batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain arsenik, ditemukan pula kandungan merkuri sebesar 0,3 mg/kg dan kadmium sebesar 0,2 mg/kg.
Ketiga logam berat ini dikenal sebagai racun lingkungan yang dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan ekosistem laut.
Kandungan logam berat tersebut berpotensi mencemari biota laut yang menjadi sumber pangan utama masyarakat pesisir Sangihe. Greenpeace mencatat bahwa ikan-ikan yang ditangkap di sekitar wilayah terdampak menunjukkan jejak kontaminasi logam berat, yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan saraf, kerusakan ginjal, dan penyakit kronis lainnya.
Dalam konteks pulau kecil yang bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan, pencemaran ini bukan sekadar ancaman lingkungan, tetapi juga krisis pangan dan kesehatan masyarakat.
Dampak pencemaran ini diperparah oleh aktivitas pertambangan yang membuka lahan secara masif, menyebabkan deforestasi dan sedimentasi tinggi di wilayah pesisir.
Ketika vegetasi hilang, tanah menjadi mudah tererosi dan terbawa ke laut, mempercepat proses pencemaran dan merusak habitat terumbu karang serta jalur migrasi spesies laut. Sangihe, yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dunia dan jalur migrasi tuna global, kini berada dalam tekanan ekologis yang akut.
Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam ketahanan pangan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Pencemaran ini juga pada akhirnya menjelma ancaman terhadap ekosistem global.
Jika pencemaran terus dibiarkan, maka kerusakan yang terjadi akan melampaui batas geografis dan berdampak pada keseimbangan ekologis lintas negara.
Oleh karena itu, penghentian total aktivitas tambang dalam bentuk apapun, yang diiringi dengan pemulihan ekosistem Sangihe harus menjadi prioritas dalam agenda perlindungan lingkungan nasional dan internasional.
Topik:
Jatam Rusak Sangihe Dirundung Tambang Greenpeace Indonesia KontraS Save Sangihe Ikekendage Diaspora SangiheBerita Terkait

Nikel dari Tanah Terampas: Kriminalisasi Warga dan Pertarungan Kuasa Antar-Korporasi di Halmahera
10 November 2025 19:20 WIB

JATAM Rilis "Konflik Kepentingan di Balik Gurita Bisnis Gubernur Maluku Utara", Begini Isinya
30 Oktober 2025 13:30 WIB

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!
23 Oktober 2025 15:13 WIB