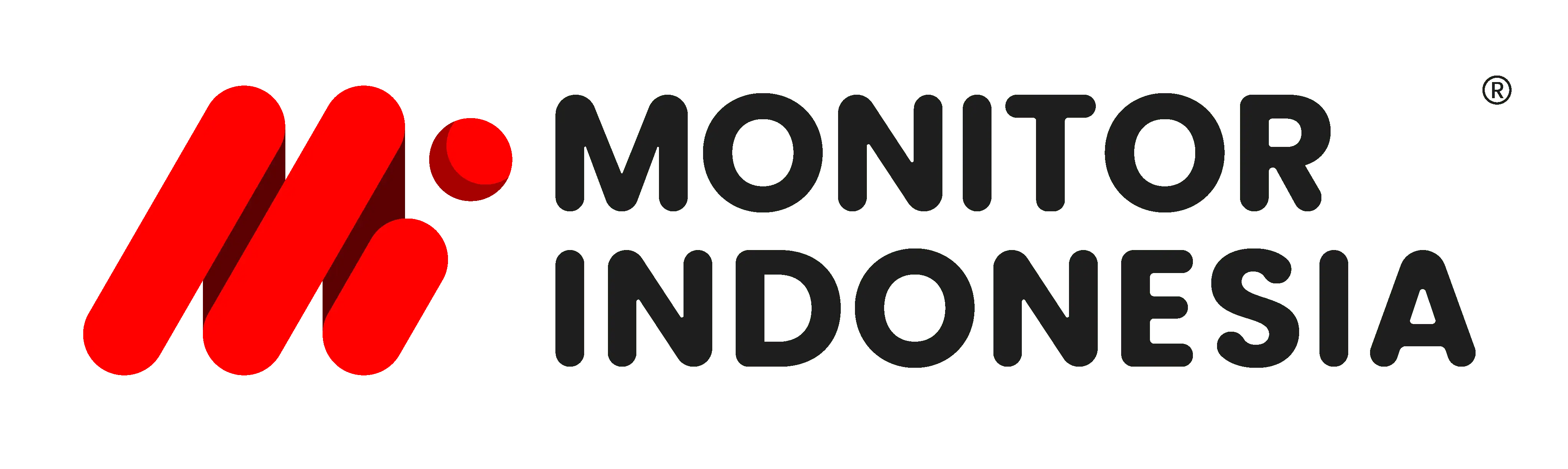Dibalik Kecepatan Whoosh, Ada Risiko Fiskal yang Mengintai

Jakarta, MI - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan terkait potensi risiko fiskal yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengamat menilai, jika pengelolaan proyek tidak terkendali, utang yang seharusnya ditanggung secara business-to-business (B to B) berisiko beralih menjadi tanggungan keuangan negara.
Awalnya, proyek Whoosh didanai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 75% dan ekuitas konsorsium China 25%. Di Indonesia, pendanaan ditanggung oleh konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin PT KAI. Angka pinjaman awal diestimasi sekitar $4,5 miliar USD dari total estimasi biaya $5–6 miliar USD.
Namun, seiring berjalannya waktu, biaya proyek membengkak menjadi sekitar US$7,5 miliar, belum termasuk dampak depresiasi nilai tukar rupiah dan perlambatan proyek akibat pandemi COVID-19.
Ekonom dan Direktur Program INDEF, Eisha M. Rachbini, Ph.D., menyoroti perubahan kebijakan yang krusial, yaitu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 172/2015 pada 2021, yang membuka ruang bagi dukungan fiskal APBN, menyalahi janji awal skema B to B murni.
Pada 2023, muncul Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,3 triliun kepada PT KAI yang berfungsi sebagai jaminan pemerintah atas pinjaman tambahan dari CDB. Eisha memaparkan data kerugian konsisten pada PSBI: minus Rp0,97 triliun pada 2023, minus Rp4,2 triliun pada 2024, dan diproyeksikan minus Rp1,6 triliun pada 2025. Kerugian ini, yang 60% merupakan beban PT KAI, menunjukkan tekanan pembiayaan yang belum teratasi dan menciptakan risiko fiskal pada keuangan negara.
Meskipun kinerja operasional Whoosh menunjukkan adanya penumpang (dengan rekor harian pada Juni 2025), Eisha mencatat adanya gap 40% okupansi dari target ideal 36 ribu penumpang harian. Ia menutup dengan menyoroti penolakan Kementerian Keuangan untuk membiayai utang menggunakan APBN, mendorong munculnya opsi restrukturisasi utang, konversi utang menjadi ekuitas, dan negosiasi dengan CDB, termasuk opsi penambahan dana melalui lembaga seperti Danantara.
Muhamad Rosyid Jazuli, peneliti dari PPPI, menilai bahwa polemik KCIC lebih mencerminkan isu politik yang dibesar-besarkan ketimbang persoalan ekonomi berskala besar. Ia membandingkan utang Whoosh yang relatif menengah hanya seperempat dari anggaran subsidi BBM atau jauh di bawah anggaran kementerian besar tetapi mendapat sorotan berlebihan (spotlight) karena dimensi politiknya.
Rosyid menyebut isu ekonomi politik ini memiliki ciri khas diperkeruh oleh komunikasi publik yang ala kadarnya. Ia mencontohkan adanya ketidaksinkronan komunikasi antar menteri dan pejabat yang membuat pemerintah terkesan tidak fokus dan rapuh.
"Whoosh adalah mimpi buruk ekonomi politik," tegas Rosyid. Ia menilai ukuran proyek yang relatif menengah (size menengah) justru menjadi bola panas politik yang berpotensi mengganggu legitimasi pemerintah. Rosyid menekankan perlunya pemerintah mencakup semua aspek masalah, tidak bisa hanya memilih satu akar masalah. Ia juga mengkritik sikap pemerintah yang terlihat inkonsisten dan terkesan menganggap ringan masalah KCIC, yang bisa merusak kepercayaan publik.
Pelajaran penting yang harus diambil, menurut Rosyid, adalah perlunya perencanaan yang lebih baik, pelibatan swasta, transparansi yang lebih ketat, dan pengawasan tata kelola proyek. Rosyid juga mengingatkan bahwa proyek infrastruktur jangka panjang (10–25 tahun) sering kali berbenturan dengan siklus politik 5 tahunan di Indonesia.
Terakhir, ia mengingatkan agar pemerintah berkomunikasi kuat dengan Tiongkok untuk menghindari risiko tuduhan mengambil alih aset dan menegaskan bahwa Whoosh harus dipandang sebagai barang mahal yang memiliki aspek teknologi dan governance maju, bukan sekadar objek wisata.
Dr. Handi Rizsa Idris, Wakil Rektor Universitas Paramadina, mempertanyakan urgensi proyek Whoosh, mengingat jarak Jakarta-Bandung (150 km) masih terjangkau moda transportasi lain seperti bus atau kereta reguler, sehingga belum menunjukkan tingkat kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
Ia meninjau kembali sejarah proyek yang awalnya digagas era SBY untuk rute Jakarta-Surabaya (748 km) dengan studi kelayakan yang lebih matang. Dalam perkembangannya, proposal Tiongkok yang disetujui Jokowi (Perpres 2015) memiliki nilai awal lebih rendah ($5,13 miliar USD) dari Jepang ($6,52 miliar USD), namun masalah utama timbul karena Tiongkok setuju tanpa jaminan pemerintah, skema B to B murni. Handi mengutip mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang kala itu telah menentang proyek tersebut karena dianggap tidak visible dan tidak menguntungkan.
Fakta di lapangan menunjukkan perubahan signifikan: cost overrun menyebabkan selisih utang mencapai Rp21,4 triliun. Permintaan Tiongkok agar mendapatkan jaminan dari APBN akhirnya terjadi, yang membebani PT KAI dan memunculkan PMN. Handi menilai, skema transaksi ini "mendesain sedemikian rupa 'memaksa dengan skema negara".
Mengutip analisis akademisi Faisal Basri, meski tingkat keterisian penumpang mencapai 50%, KAI masih membukukan kerugian sekitar Rp4,195 triliun dalam laporan keuangan PSBI tahun 2024. Untuk mengatasi hal ini, Handi mengusulkan beberapa strategi untuk mengatasi masalah ini, antara lain:
- Restrukturisasi Utang dan kemungkinan akuisisi aset oleh pemerintah.
- Injeksi Modal dari lembaga seperti Danantara.
- Perpanjangan Rute Whoosh hingga Surabaya untuk meningkatkan jumlah penumpang dan potensi pendapatan.
- Optimalisasi Tarif dan Integrasi dengan jaringan angkutan perkotaan dan logistik.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan.
Topik:
proyek-kereta-cepat-whoosh