Ruang Lingkup dan Keadilan Masyarakat Pulau Kabaena

Titin Kurniawati Ry - Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada

PRAKTIK pertambangan nikel di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik lokal yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan.
Masuknya korporasi tambang besar ke wilayah ini bukan sekadar akibat dari peluang investasi, melainkan hasil dari proses politik yang secara sistematis mengakomodasi kepentingan elite lokal melalui kebijakan yang cenderung abai terhadap aspek keadilan lingkungan.
Kepedulian terhadap lingkungan, korelasi antara globalisasi di berbagai sektor dan munculnya masalah lingkungan telah terbukti belakangan ini. Degradasi dan kehancuran lingkungan sering kali muncul di sepanjang perkembangan atau hasil produksi manusia dan perusahaan.
Berdasarkan penelitian yang mengkaji pendekatan keadilan ekologis untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi Indonesia atas kejahatan lingkungan menunjukkan pengaturan denda pemulihan lingkungan dalam menerapkan strategi keadilan ekologis yang berfokus pada perlindungan lingkungan (Saputra, U., & Islam 2024).
Namun, terdapat kekhawatiran terkait kepastian hukum dalam menyikapi keseimbangan antara keadilan ekologis dan kepastian hukum.
Fenomena kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan nikel memberikan dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat.
Belum adanya kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang yakni perusahaan yang melakukan produksi pertambangan, pemerintah sebagai regulator kebijakan, dan masyarakat sebagai pihak yang berdampak kerusakan lingkungan (Agussalim, A., & Saleh 2023).
Lebih jelasnya (Aldiansyah, S., & Nursalam, 2019) pada kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel jelas memberikan dampak seperti kerusakan jalan, pencemaran air sungai-laut, polusi udara, kerusakan lahan, kerusakan flora dan fauna, dan sampai dampak sosial seperti perubahan perilaku masyarakat, hingga tidak ada pemberdayaan kesehatan masyarakat.
Keadilan lingkungan (Environmental Justice) sebagai prinsip kesetaraan mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa segmen masyarakat yang rentan secara sosial tidak terpengaruh secara tidak proporsional oleh dampak atau bahaya lingkungan yang merugikan.
(Bullard RD, 1994) menjelaskan bagaimana gerakan “environmental justice”, pada dasarnya gerakan lingkungan adalah segala sesuatu: kita tinggal, bekerja, bermain, bersekolah, serta dunia fisik dan alami. Jika sulit memisahkan lingkungan fisik dari lingkungan budaya, maka seharusnya memastikan keadilan terintegrasi dalam semua hal yang dilakukan menyangkut lingkungan.
Lebih lanjut (Bullard RD, 2000) mendefinisikan environmental justice sebagai prinsip bahwa “semua orang dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan yang sama atas hukum dan peraturan lingkungan dan kesehatan masyarakat.”
Menyadari pentingnya aspek keadilan dalam konteks lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, diharapkan akan kesadaran dan kepedulian serta upaya pelestariannya yang berkelanjutan.
Munculnya perusahaan tambang pada kenyataannya tidak selalu mendatangkan manfaat positif, akan tetapi dengan adanya tambang juga berdampak negatif terhadap lingkungan seperti tercemarnya air laut akibat limbah tambang. Komunitas maritim yang memiliki relasi historis dan budaya yang erat dengan laut.
Masalah pertambangan di pulau Kabaena hadir setelah adanya revisi aturan tata ruang tahun 2010 tentang menurunkan status kawasan hutan, dari lindung menjadi hutan produksi.
Revisi ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011, yang mengubah fungsi kawasan hutan seluas 115.111 hektare di Sulawesi Tenggara termaksud pulau Kabaena. mengakibatkan banyak perusahaan tambang masuk ke pulau Kabaena. Secara keseluruhan, luas konsesi yang pernah tercatat di pulau Kabaena kurang lebih 76.438,1 hektare atau 85,79 persen dari luas pulau Kabaena.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melarang tegas aktivitas pertambangan di wilayah yang luasnya kurang dari 2.000 kilometer persegi.
Di pulau Kabaena pelanggaran terlihat jelas dari 891 kilometer persegi total luas pulau Kabaena, sekitar 650 kilometer persegi telah dikuasai tambang.
Aktivitas pertambangan nikel menyebabkan berbagai kerusakan ekologis seperti pencemaran laut, sedimentasi di kawasan terumbu karang, serta hilangnya habitat ikan, pada gilirannya mengganggu mata pencaharian nelayan bajo dan menurunkan daya dukung ekologis laut.
Selain itu, masyarakat Bajo seringkali tidak dilibatkan secara substansial dalam proses perizinan atau pengawasan proyek tambang yang menandakan adanya ketimpangan struktural dalam tata kelola lingkungan.
Hal ini memperkut asumsi bahwa, praktik pertambangan di kawasan ini mencerminkan bentuk environmental justice kelompok marjinal seperti suku Bajo menjadi pihak paling terdampak namun paling sedikit memperoleh manfaat atau perlindungan hukum.
Sebagai masyarakat adat maritim, suku Bajo berhadapan dengan hilangnya hak atas ruang laut yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan sistem kehidupan mereka.
Rentetan-rentetan pelanggaran hukum, mulai dari pemberian izin sampai eksploitasi tambang nikel memberikan dampak serius bagi masyarakat pulau Kabaena khususnya masyarakat suku Bajo.
Untuk itu, diperlukan solusi yang bersifat struktural dan partisipatif. Penguatan regulasi berbasis prinsip keadilan ekologis, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran izin tambang, serta keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup mereka.
Selain itu, pemulihan ekologis harus menjadi agenda prioritas dengan menempatkan ruang hidup masyarakat sebagai pusat dari kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan reformasi tata kelola yang transparan dan akuntabel guna memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak komunitas lokal.
Topik:
UGM Kabaena Sultra Titin Kurniawati RyOpini Sebelumnya
Permenkes KRIS Tidak Boleh Bertentangan dengan UU dan Perpres
Opini Selanjutnya
Prabowo Harus Segera Mengganti Menteri "Duri dalam Daging"
Opini Terkait

Pembentukan Kodam Sultra dan Mako Grup 5 Kopasus Bukan Sekadar Pertahanan dan Keamanan Nasional tapi Kebutuhan Geopolitik
19 Oktober 2025 02:25 WIB

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Tambang di Kabaena Seret Gubernur Sultra
15 September 2025 18:09 WIB
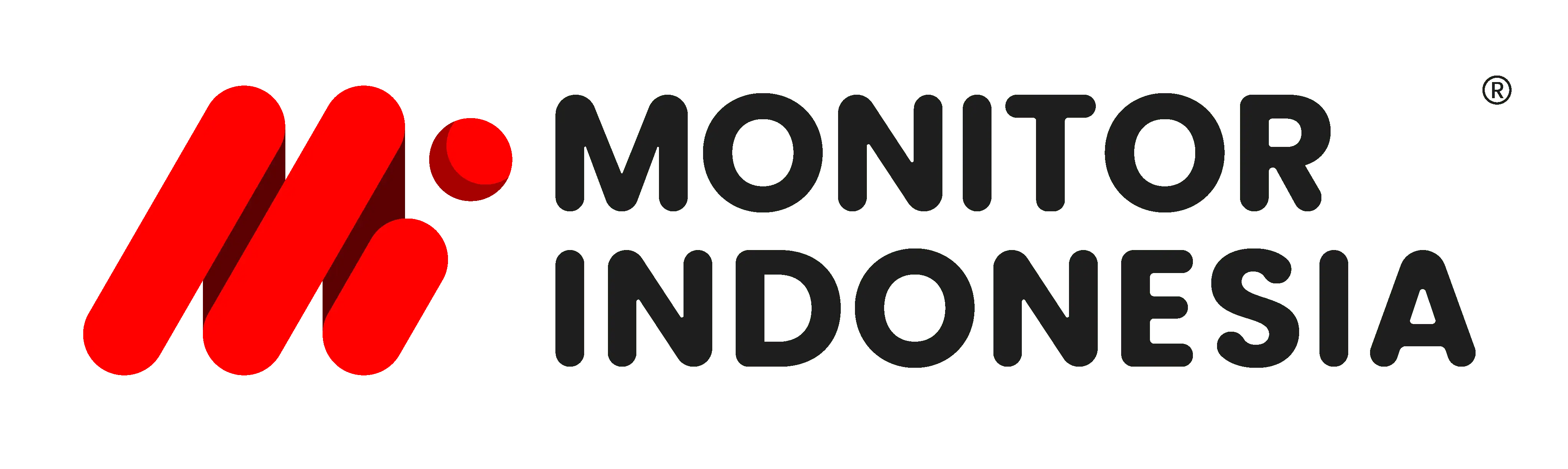


![UGM Nonaktifkan Dwi Hartono Otak Pembunuhan Kacab Bank BUMN Gedung Universitas Gajah Mada [Foto: Ist]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ugm-1.webp)
