Mantan Presiden vs Narasi Palsu: Ketika Privasi dan Akuntabilitas Publik Bertarung
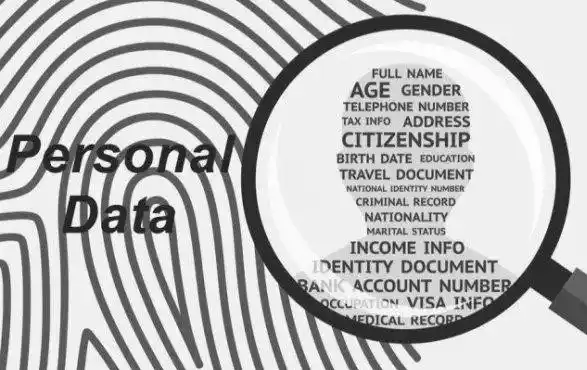
Jakarta, MI - Dalam filsafat hukum, privasi adalah hak asasi yang melekat pada setiap individu, termasuk figur publik. Namun, akuntabilitas pemimpin juga menjadi prinsip demokrasi.
"Jokowi sebagai mantan presiden berhak membela reputasinya, tetapi masyarakat juga berhak mempertanyakan integritas pemimpinnya. Polemik ini mencerminkan tarik-menarik antara hak individu (privasi) dan kepentingan publik (transparansi)," kata Sidi Ahyar Wiraguna, pemerhati hak privasi dan pelindungan data pribadi kepada Monitorindonesia.com, Minggu (11/5/2025).
Filosofi Immanuel Kant tentang "keberanian mengetahui" (sapere aude) relevan di sini: kebenaran harus diungkap secara proporsional, tanpa mengorbankan keadilan bagi pihak yang dituduh.
Kepastian hukum dan perlindungan data
Secara hukum, UU PDP dan KUHP melindungi privasi sekaligus menjamin proses hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu. Jika tuduhan ijazah palsu terbukti fitnah, pelapor bisa dijerat Pasal 14 UU No. 1/1946 atau Pasal 45A UU ITE.
"Namun, jika ada indikasi pelanggaran data pribadi (seperti penyebaran dokumen tanpa izin), Jokowi berhak mengajukan gugatan," ungkapnya.
Penting dicatat, bahwa statusnya sebagai mantan presiden tidak menghilangkan hak hukumnya, tetapi juga tidak memberinya kekebalan dari pemeriksaan.
"Kepolisian harus bekerja independen, mengutamakan bukti, bukan tekanan politik," katanya.
Polarisasi dan etika bermedia
Polemik ini memperlihatkan polarisasi masyarakat yang kerap mempolitisasi isu pribadi. Tuduhan tanpa bukti—seperti kasus Umar Kholid—merusak iklim diskusi sehat.
Di sisi lain, respons lambat Jokowi selama ini bisa dimaknai sebagai strategi menghindari eskalasi konflik. Namun, sebagai mantan presiden, langkah hukumnya kini bersifat personal, bukan politis. Masyarakat perlu belajar memisahkan antara kritik substantif dan narasi provokatif.
"Media pun harus berperan sebagai penyeimbang dengan verifikasi fakta, bukan amplifikasi sensasi," tegasnya.
Refleksi pascakekuasaan
Status Jokowi yang kini menjadi warga negara biasa menggeser konteks polemik ini dari ranah politik ke ranah hukum murni. Upayanya melapor ke polisi adalah bentuk penegasan hak individu, tetapi juga ujian bagi penegak hukum untuk bersikap adil.
Pelajaran terbesar adalah pentingnya budaya "check and recheck" sebelum menyebarkan informasi, serta kesadaran bahwa di era digital, privasi dan reputasi adalah aset yang rentan.
"Pilihan Jokowi untuk tidak diam lagi patut diapresiasi sebagai langkah menuju kepastian hukum, selama prosesnya transparan dan imparsial," katanya.
Sementara itu pakar hukum pidana dari Univeristas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf, menegaskan bahwa UU PDP sudah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran.
Namun, sampai saat ini turunan UU PDP yang seharusnya secara detail membahas sanksi yang dapat dijatuhkan tidak hanya kepada pihak swasta.
Akan tetapi juga, kepada pihak pemerintah, tidak ada perkembangannya. "Juga Lembaga/Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang seharusnya sudah dibentuk Jokowi kala itu sebelum habis masa jabatannya, tidak kunjung terbentuk," kata Hudi.

Adapun sejumlah individu yang menyebarkan informasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu telah dijerat dengan ketentuan pidana.
Salah satu kasus menonjol melibatkan Umar Kholid Harahap, yang ditangkap pada Januari 2019 oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena menyebarkan konten digital yang menyatakan ijazah Jokowi tidak sah.
Ia dijerat dengan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta Pasal 207 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai tiga tahun penjara.
Kasus lainnya adalah gugatan dan penyebaran informasi palsu oleh Bambang Tri Mulyono. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Solo memvonis Bambang dengan hukuman enam tahun penjara karena terbukti menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran publik. Ia dijerat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Bambang sebelumnya juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuding bahwa Jokowi mencalonkan diri dalam pemilu dengan menggunakan ijazah palsu. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan karena tidak memiliki dasar fakta dan bukti hukum yang kuat.
Hudi melanjutkan bahwa meskipun tuduhan terhadap Presiden Jokowi tidak terbukti dan dibantah secara resmi oleh institusi pendidikan, proses hukum terhadap penyebar hoaks tetap penting untuk menjaga marwah hukum dan informasi publik yang benar.
Di lain sisi, tegasnya, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyaring dan membagikan informasi, khususnya yang menyangkut integritas pejabat negara.
"Kritik terhadap pejabat publik adalah hal wajar, tetapi harus dilakukan berdasarkan data dan argumen yang sah, bukan berdasarkan dugaan tanpa dasar hukum," ungkapnya.
Menurut Hudi, kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi menjadi pembelajaran penting dalam membedakan antara kritik sah dengan penyebaran fitnah.
"Sistem hukum kita telah memberikan sanksi tegas terhadap perbuatan pemalsuan dokumen maupun penyebaran hoaks, guna melindungi integritas data publik dan tatanan hukum negara," tandas Hudi.
Topik:
Data Pribadi Jokowi Ijazah Palsu PDP Ijazah JokowiBerita Terkait

Prabowo Resmikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia, Wujud Inisiatif Jokowi
19 November 2025 12:41 WIB

KPU Surakarta Musnahkan Arsip Dokumen Jokowi saat Cawalkot, Roy Suryo Singgung UU KIP
18 November 2025 06:54 WIB

Kuasa Hukum Yakin Roy Suryo Cs Tidak Akan Ditahan, Singgung Firli Bahuri dan Silfester Matutina
13 November 2025 14:43 WIB




