Kebebasan yang Masih Terkekang: Harapan dan Bahaya di Balik Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi sorotan publik setelah mengabulkan sebagian uji materi Pasal 315 KUHP terkait penghinaan ringan. Meski membuka peluang baru bagi perlindungan kebebasan berekspresi, putusan ini masih menyisakan sejumlah kekhawatiran, khususnya dalam konteks perlindungan aktivis dan pembela hak asasi manusia.
Kasus yang melatari uji materi ini diajukan oleh Daniel Frits, seorang aktivis lingkungan di Jepara, yang menghadapi proses hukum akibat kritiknya terhadap proyek industri ekstraktif. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap pasal-pasal karet yang kerap digunakan untuk membungkam suara kritis di ruang publik.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 315 KUHP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai secara terbatas dengan memperhatikan konteks, intensi, dan dampak dari pernyataan yang dianggap menghina. Putusan ini bersifat conditionally unconstitutional, artinya pasal tersebut masih berlaku selama interpretasinya mengikuti pedoman yang ditetapkan Mahkamah, sambil menunggu revisi dari pembentuk undang-undang.
Namun, di sinilah letak persoalan. Pedoman interpretatif seperti “konteks” dan “dampak” bukanlah istilah hukum yang memiliki kepastian. Dalam praktik, interpretasi tersebut sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum, yang tidak selalu memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Akibatnya, celah penyalahgunaan pasal tetap terbuka lebar.
Putusan ini tentu layak diapresiasi sebagai pengakuan formal terhadap pentingnya kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun dalam implementasinya, langkah ini belum cukup untuk mengakhiri praktik kriminalisasi terhadap aktivis. Sejumlah laporan dari Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa pasal-pasal serupa terus digunakan untuk menjerat warga yang bersuara kritis terhadap kekuasaan.
Persoalan kian kompleks karena revisi KUHP—yang menjadi tanggung jawab DPR dan Pemerintah—bukan perkara mudah. UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP warisan kolonial saja masih menyisakan kontroversi dan belum sepenuhnya berlaku efektif. Dengan agenda politik yang padat pasca Pemilu 2024, besar kemungkinan pembahasan revisi pasal-pasal semacam ini akan kembali tersingkir dari prioritas legislasi nasional.
Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memilih jalur kompromi: tidak membatalkan pasal secara penuh, namun juga tidak memberi kepastian hukum yang memadai bagi perlindungan warga negara. Pendekatan ini, meskipun bersifat progresif secara narasi, berisiko menjadi solusi setengah matang yang menyisakan kerentanan di lapangan.
Ke depan, perlindungan kebebasan berekspresi memerlukan langkah konkret. Pertama, DPR harus segera menindaklanjuti putusan ini dengan revisi pasal yang memuat batasan yang ketat dan objektif. Kedua, penegak hukum perlu dibekali pelatihan berperspektif hak asasi manusia agar tidak menyalahgunakan instrumen hukum pidana. Ketiga, literasi publik tentang kebebasan berekspresi harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh klaim penghinaan yang bersifat subjektif.
Putusan ini adalah awal yang baik, namun belum cukup untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap suara-suara kritis. “Jika hukum adalah pedang, maka keadilan adalah tangan yang menggenggamnya. Putusan MK ini mungkin mengasah pedangnya, tapi siapa yang memegang dan mengayunkan tetap tergantung pada kekuatan masyarakat sipil.”. (Irwn)
Topik:
Mahkamah KonstitusiBerita Terkait

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut
1 Oktober 2025 19:23 WIB

Arsul Sani Serukan Keadilan Iklim dalam Forum J20 Summit 2025 di Johannesburg
5 September 2025 19:50 WIB
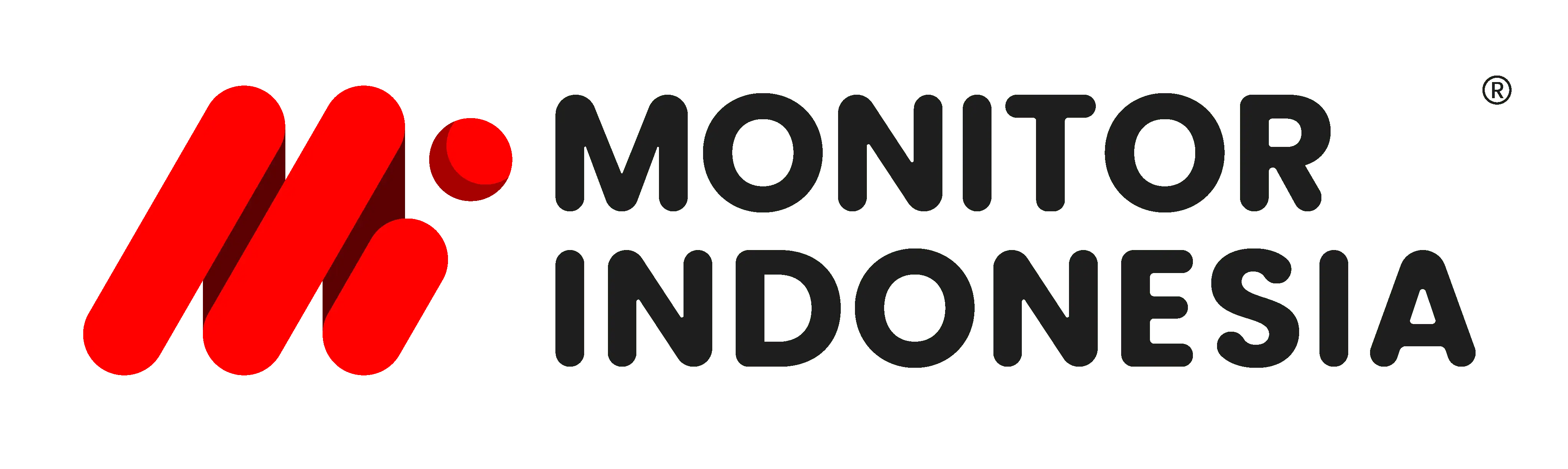


![Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Gedung Mahkamah Konstitusi [Foto: Doc. MI]](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/mahkamah-konstitusi-mk.webp)
