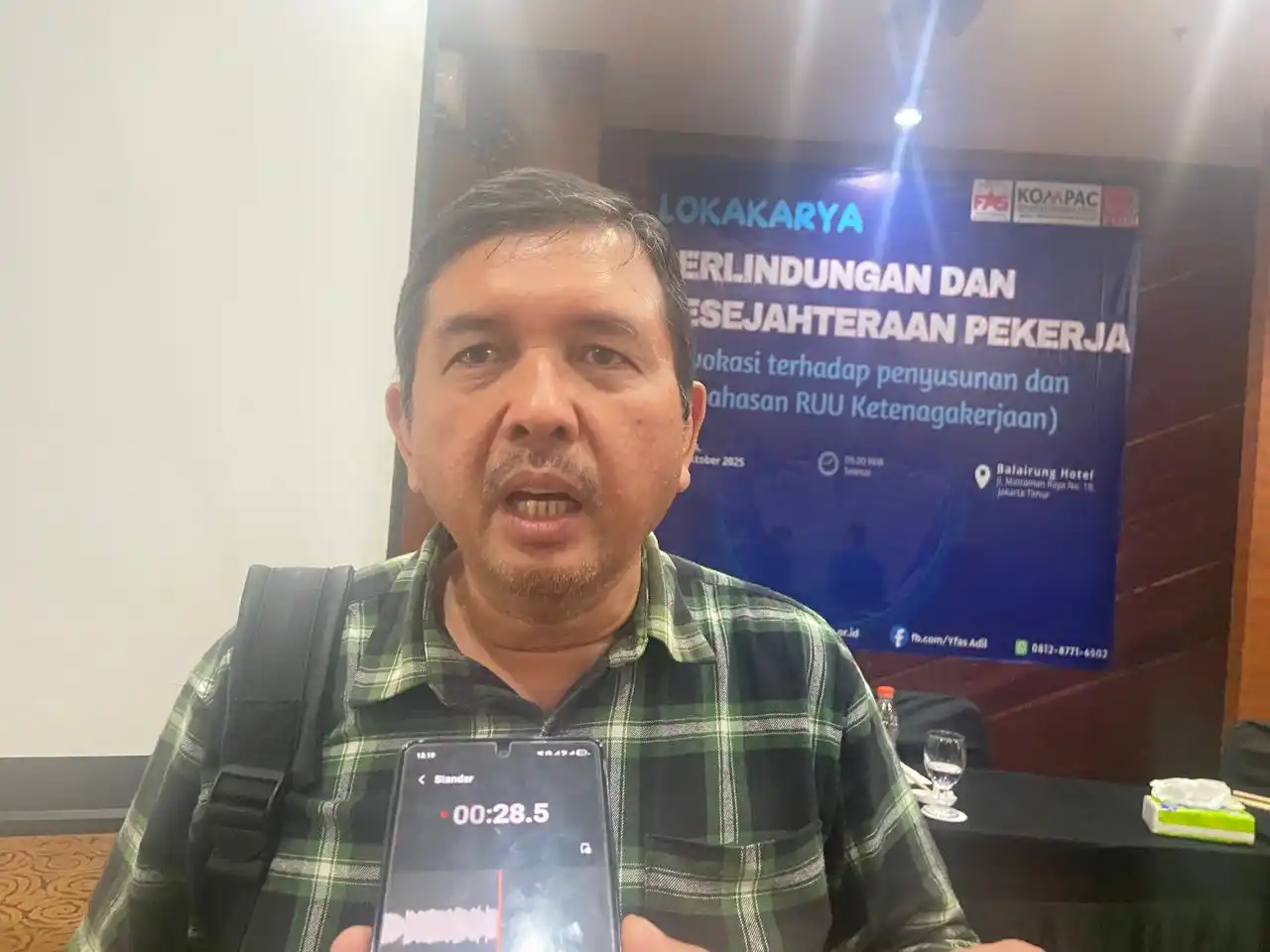Angka Kemiskinan Diragukan, Celios Ingatkan Dampak Serius pada Penyaluran Bansos

Jakarta, MI - Data kemiskinan terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menuai kritik. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan pemerintah, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
BPS mencatat, per Maret 2025 jumlah penduduk miskin tercatat 8,47 persen dari total populasi atau sekitar 23,8 juta orang. Angka ini turun tipis 0,1 persen poin dibandingkan data September 2024.
Namun Bhima menilai, kenyataannya jauh berbeda. Menurutnya, penduduk miskin di lapangan sebenarnya jauh lebih banyak dari data resmi pemerintah.
Bhima menyoroti adanya ketimpangan besar antara data kemiskinan versi pemerintah Indonesia dan laporan lembaga internasional. Mengacu pada data terbaru Bank Dunia, sekitar 68,2 persen penduduk Indonesia, setara dengan 194,4 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan internasional.
Menurunya, angka tersebut sangat jauh berbeda dengan data resmi BPS yang mencatat hanya 8,57 persen atau 24,06 juta orang yang dikategorikan miskin. Meski metodologi keduanya berbeda, disparitas sebesar 8 kali lipat ini menunjukkan ada masalah dalam cara mendefinisikan kemiskinan.
Terlebih lagi, Bhima menilai BPS masih menggunakan metode pengukuran kemiskinan yang sudah ketinggalan zaman. Selama hampir lima dekade, pendekatan yang dipakai berbasis pada tingkat pengeluaran dan komponen kebutuhan yang dinilainya sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Angka kemiskinan selama menggunakan metode garis kemiskinan yang lama tidak akan menjawab realita di lapangan. Jadi BPS kalau masih keluarkan angka kemiskinan tanpa revisi garis kemiskinan sama saja datanya kurang valid.” ujarnya, sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya pada Minggu (27/7/2025).
Ia mengungkapkan masalah fundamental data kemiskinan berdampak pada pengambilan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh klaim pemerintah terkait keberhasilan perlindungan sosial, program pertanian, MBG, dan hilirisasi tidak sepenuhnya tercermin dari data BPS.
Bhima menambahkan akibat data BPS tidak bisa jadi acuan program bantuan sosial karena masalah keakuratan data membuat pemerintah mengeluarkan anggaran lebih besar untuk identifikasi penerima manfaat.
"Seharusnya data BPS bisa dipakai untuk program pengentasan kemiskinan, tapi pemerintah harus mencari data sendiri by name by address untuk memetakan orang miskin menurut kriteria yang beda dengan BPS” kata Bhima.
Bhima juga menekankan pentingnya reformasi dalam metodologi pengukuran kemiskinan nasional. Ia mencontohkan bahwa negara-negara seperti Malaysia dan Uni Eropa telah rutin memperbarui pendekatan mereka agar selaras dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
Menurutnya, Indonesia perlu mengikuti jejak tersebut. Meski begitu, perubahan ini memerlukan keberanian politik dari pemerintah.
Ia pun mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan pendekatan baru dalam memaknai kemiskinan secara lintas sektoral. Perpres ini nantinya akan menjadi dasar bagi integrasi data, sinkronisasi indikator, dan penyesuaian seluruh program pengentasan kemiskinan ke depan.
Namun demikian, langkah tersebut hanya mungkin dilakukan jika data kemiskinan tidak lagi dipolitisasi. Selama angka kemiskinan hanya digunakan untuk kepentingan pencitraan atau legitimasi politik, maka reformasi metodologi hanya akan menjadi retorika.
Sebagai alternatif, Bhima mengusulkan agar ukuran kesejahteraan tidak lagi berbasis total pengeluaran, tetapi pada pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income), yakni pendapatan bersih yang tersedia setelah dikurangi kewajiban pokok seperti pajak dan kebutuhan dasar.
Pendapatan disposabel mencerminkan kondisi akhir setelah negara menjalankan peran redistributifnya, baik melalui pungutan maupun transfer sosial.
"Dengan membandingkan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah intervensi fiskal, kita dapat menilai seberapa efektif kebijakan negara dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, sehingga kita tahu mana program yang harus dilanjutkan, mana yang harus dihentikan," jelas Bhima.
Dalam waktu yang bersamaan, Bhima menilai bahwa indikator kesejahteraan masyarakat lainnya juga perlu dipertimbangkan secara terpadu dalam evaluasi pembangunan.
Indikator tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, perumahan dan kesehatan, upah yang layak, jaminan hari tua, angka pengangguran dan PHK, hingga, tingkat kejahatan dan korupsi.
Namun saat ini, menurutnya, pemerintah cenderung hanya menyoroti data-data yang bernuansa positif dengan dasar metodologi yang kurang kuat, dan pada saat yang sama mengabaikan indikator penting lainnya.
"Kita lebih baik menggunakan data dengan benar untuk melihat fakta yang ada, ketimbang memoles data hanya untuk kepentingan pencitraan, yang ujung-ujungnya malah membingungkan perencanaan kebijakan ke depannya. Kemiskinan bukan aib, tapi masalah sosial yang harus diselesaikan," pungkasnya.
Topik:
angka-kemiskinan bps celios bhima-yudhistira