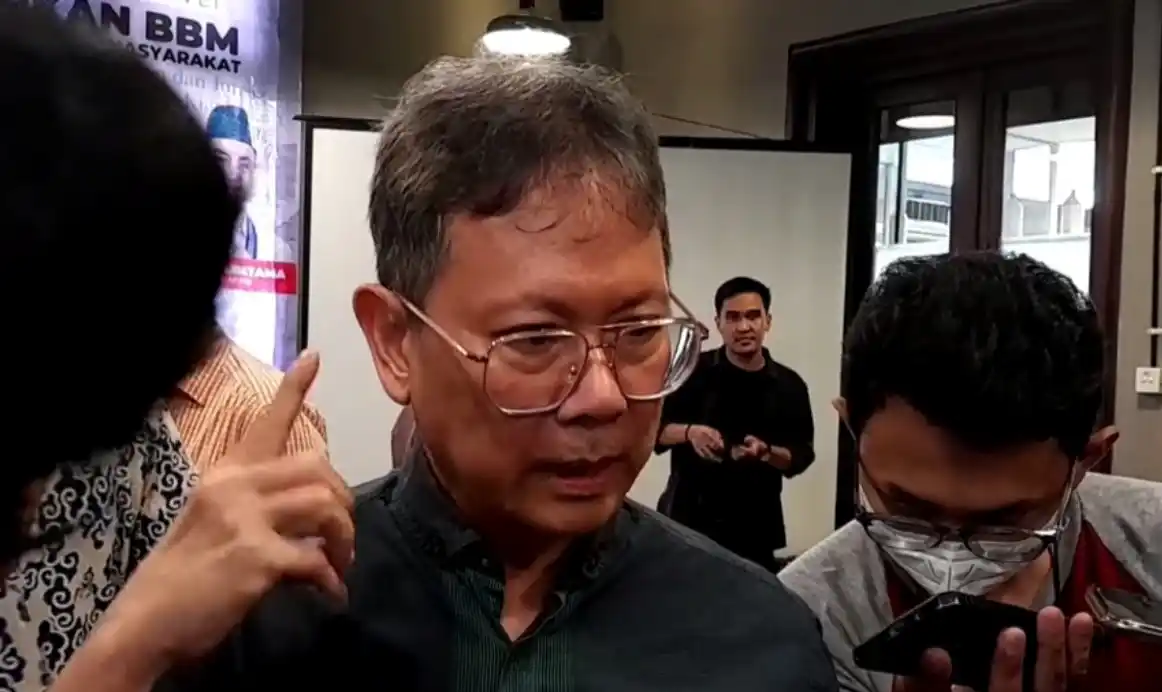"Presidential Threshold" dan Peran DPD dalam Percaturan Politik Nasional
Nicolas
Diperbarui
10 Juli 2022 16:51 WIB

Topik:
DPD pemilu 2024 Pilpres 2024